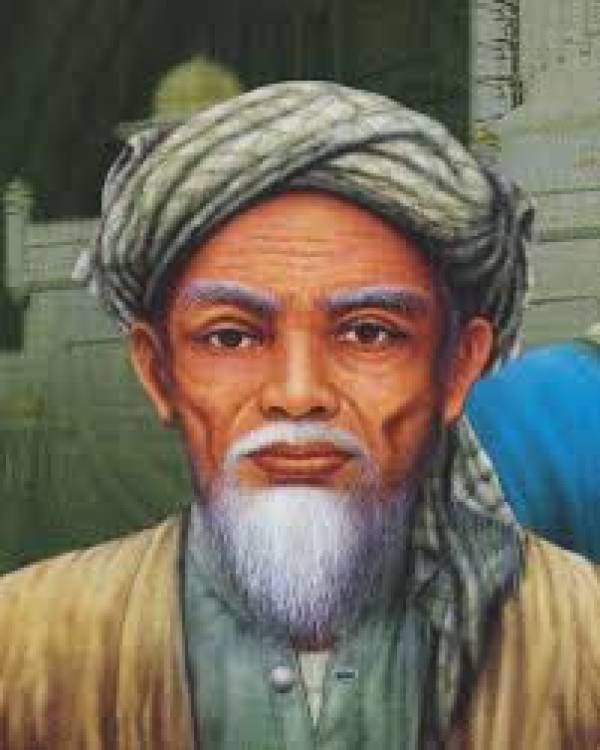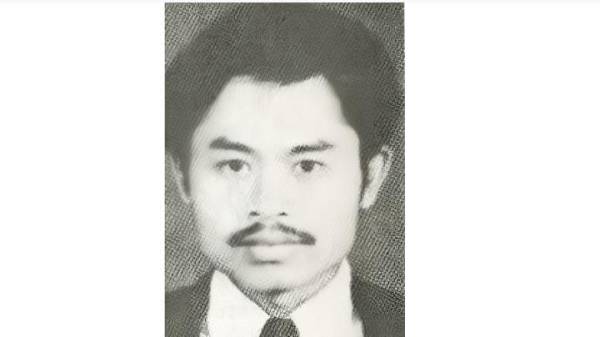SURABAYA, PustakaJC.co - Sunan Bonang merupakan putra Sunan Ampel, dari pernikahan dengan putri Arya Teja Bupati Tuban bernama Nyai Ageng Manila.
Sunan Bonang dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang pandai dalam berdakwah. Ia menguasai ilmu tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan berbagai ilmu kesaktian.
Dakwah yang dilakukan Sunan Bonang berawal di daerah Kediri, yang menjadi pusat ajaran Bhairawa-Tantra dengan membangun masjid di Singkal, yang berada di sebelah barat Kediri.
Sunan Bonang mengembangkan dakwahnya di pedalaman. Yang mana masyarakatnya masih menganut ajaran Tantrayana.
Dakwahnya pun berlanjut ke daerah Lasem. Dalam mengajarkan Islam, Sunan Bonang memanfaatkan media wayang, tasawuf, tembang, dan sastra sufistik.
Berikut ini perjalanan hidup Sunan Bonang, sebagaimana dikutip dari buku Atlas Wali Songo karya Agus Sunyoto.
Asal-usul dan Nasab Sunan Bonang
Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dari pernikahannya dengan Nyai Ageng Manila. Ia, anak keempat dari enam bersaudara. Saudaranya yakni Nyai Patimah, Nyai Gedeng Panyuran, Nyai Wilis, Nyai Taluki, dan Raden Qasim (Sunan Drajat).
Dalam buku Het Book van Bonang, diperkirakan Sunan Bonang lahir sekitar tahun 1465 Masehi, dengan nama kecil Mahdum Ibrahim. Selain saudara seibu, Sunan Bonang juga memiliki beberapa saudara dari lain ibu. Mereka yakni Dewi Murtosiyah, Dewi Murtosimah, Seh Mahmud, Seh Saban, Nyai Mandura, dan Nyai Piah.
Sunan Bonang memiliki nasab dari Nabi Muhammad SAW, melalui Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Menurut naskah sejumlah historiografi, Sunan Bonang memilih nasab dari galur laki-laki yang merujuk ke Sammarkand, Uzbekistan.
Sementara menurut naskah Klenteng Talang, Sunan Bonang merupakan wali keturunan asing dari Yunan di Cina Selatan, dengan nama asli Bong Ang. Berdasarkan pemerolehan informasi dari segala sumber menunjuk bahwa Sunan Bonang adalah keturunan asing yang mendapatkan pendidikan Jawa.
Pendidikan dan Pengembangan Keilmuan Sunan Bonang
Sunan Bonang belajar pengetahuan dan ilmu agama dari Sunan Ampel bersama santri-santri lainnya. Seperti Sunan Giri, Raden Patah, dan Raden Kusen. Ia juga berguru dengan Syaikh Maulana Ishak dalam perjalanan haji ke Tanah Suci.
Sunan Bonang dikenal sebagai seorang penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, ushuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu sifat dengan kesaktian. Bahkan, masyarakat mengenangnya sebagai seseorang yang sangat pandai mencari sumber air di beberapa tempat yang mengalami kekurangan air.
Menurut Serat Kandhaning Ringgit Purwa dalam naskah LOr 6379 No. 9, Sunan Bonang disebut mempunyai keistimewaan yang luar biasa dari kewaliannya. Di mana ia bisa menjagokan seekor anak ayam ketika ditantang untuk sabung ayam oleh Ajar Blacak Ngilo.
Babad Daha-Kediri menggambarkan sosok Sunan Bonang dengan pengetahuannya yang luar biasa, dapat mengubah aliran Sungai Brantas. Sehingga menjadikan daerah yang menolak dakwah Islam di sepanjang aliran sungai menjadi kekurangan air. Bahkan sebagian yang lain mengalami banjir.
Sunan Bonang dalam menyebarkan dakwahnya lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat seni dan budaya. Sebagaimana dilakukan oleh Sunan Kalijaga, muridnya.
Sunan Bonang menjadi dalang dalam pertunjukan wayang, dan menggubah tembang macapat. Ia juga banyak mempelajari kesenian dan budaya Jawa.
Sunan Bonang menulis naskah Primbon Bonang yang memuat ajaran esoteris doktrin dan ajaran inti tasawuf yang mendalam. Selain itu, ia juga menulis Suluk Wujil atau kitab yang berisi pengetahuan tasawuf yang lebih dalam dan rahasia (esoteris).
Ungkapan Suluk Wujil tergolong rahasia karena menyangkut bahasan hakikat Ketuhanan yang diungkapkan dalam pupuh berlanggam dhandhanggula.
Lika-liku Dakwah Sunan Bonang
Menurut Babad Daha-Kediri, Sunan Bonang mengawali perjalanan dakwahnya di pedalaman Kediri dengan menggunakan pendekatan yang cenderung bersifat kekerasan. Ia merusak arca yang dipuja penduduk, bahkan mengubah aliran air Sungai Brantas dan mengutuk penduduk suatu desa karena kesalahan salah seorang warga.
Dalam menyebarkan dakwahnya, Sunan Bonang membangun langgar atau musala pertama di tepi barat Sungai Brantas. Tepatnya di Desa Singkal.
Akibatnya, Sunan Bonang menghadapi resistensi dari penduduk Kediri berupa perdebatan maupun pertarungan fisik dengan Ki Buto Locaya dan Nyai Plencing. Mereka merupakan tokoh penganut ajaran Bhairawa-bhairawi di Kediri.
Atas perintah Raden Patah, Sunan Bonang pergi ke Demak untuk menjadi imam Masjid Demak. Di sinilah ia diberi gelar Sunan Bonang yang bermakna guru suci yang berkediaman di Desa Bonang, Demak. Selang beberapa saat, ia pun meninggalkan kedudukannya sebagai imam Masjid Demak.
Tahun 1480 M, Sunan Bonang berpindah ke bagian belakang dalem Kadipaten Lasem, kediaman kakak kandungnya yang bernama Nyai Gede Maloka. Sepeninggalan suaminya bernama Pangeran Wirabjra, Nyai Gede Maloka mengambil alih bagian dari pemerintahan di dalem Kadipaten.
Ia memerintahkan Sunan Bonang untuk merawat makam nenek mereka yang berasal dari Champa. Sunan Bonang juga diperintah untuk merawat makam Pangeran Wirabjra dan putranya.
Bentuk baktinya terhadap mendiang neneknya yang berasal dari Champa itu, ditunjukkan oleh Sunan Bonang dengan dibuatnya tempat sujud dari sebuah batu gilang, tepat berada di dekat makam sang nenek.
Tugas Sunan Bonang merawat makam neneknya di Puthuk Regol, melahirkan legenda mengenai petilasan pesujudan Sunan Bonang di Bukit Watu Layar, di timur Kota Lasem. Atau dikenal dengan nama Desa Bonang.
Sunan Bonang pun membangun sebuah zawiyah atau semacam tempat khusus untuk khalwat. Tempat itu digunakan sebagai tempat pertemuan para pengamal ajaran tasawuf di Puthuk Regol.
Pada usia 30 tahun, Sunan Bonang menempati kedudukan sebagai wali negara Tuban yang bertugas mengurus berbagai hal menyangkut keagamaan Islam. Dalam berdakwah, Sunan Bonang menggunakan media kesenian dan kebudayaan untuk menarik perhatian masyarakat. Salah satunya perangkat gamelan Jawa bernama Bonang yang bermakna induk kemenangan.
Dalam proses reformasi seni pertunjukan wayang, Sunan Bonang menjadi dalang yang mengajarkan ajaran rohani melalui pergelaran wayang. Sunan Bonang juga telah menyempurnakan susunan gamelan atau menggubah irama lagu-lagu. Salah satu gubahannya dalam tembang macapat yang populer adalah Kidung Bonang dalam pupuh Durma.
Sunan Bonang juga menambahkan ricikan yang terdiri atas kuda, gajah, harimau, garuda, kereta perang, dan rampogan dalam pengembangan pertunjukan wayang, sehingga memperkaya pergelaran wayang.
Berdasarkan naskah Sadjarah Dalem, Sunan Bonang diberikan sebutan Anyakrawati atau Cakrawati, karena telah memulai tradisi lingkaran kenduri atau slametan yang diambil dari upacara pancamakara. Dari sumber yang sama, dikisahkan Sunan Bonang tidak menikah sampai wafatnya. (int)