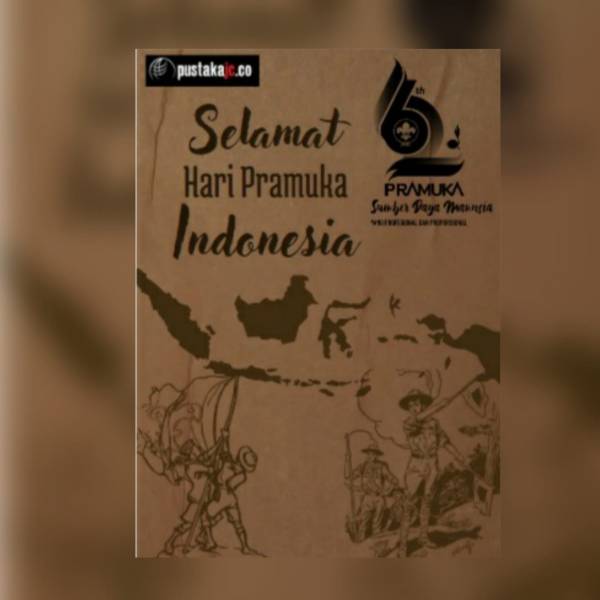Berbicara perempuan, selalu lekat dan awet dengan sebuah perdebatan atas bahasan patriarki, yaitu sebuah sistem sosial yang menempatkan perempuan pada tingkatan kedua atau dengan kata lain laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Dimana menurut Sylvia Walby (1993) yang membagi patriarki menjadi dua, yaitu patriarki privat dan patriarki publik menyebutkan bahwa telah terjadi ekspansi wujud patriarki, dari ruang-ruang pribadi dan privat seperti keluarga dan agama ke wilayah yang lebih luas yaitu negara. Anggapan patriarki inilah yang kemudian menjadi sumber atas pandangan minor terhadap perempuan.
Kembali jauh ke belakang, sejatinya narasi patriarki telah dimulai semenjak zaman Adam dan Hawa, bagaimana Hawa dipandang kala itu menjadi sumber masalah atas kekhilafannya menggodai sang Adam. Bergeser ke tanah Jawa, sebuah obrolan lazim mengungkapkan,“Nek wedok iku, yo umbah-umbah karo korah-korah” (Kalau perempuan itu, ya nyuci pakaian dan piring). Kalimat tersebut menjadi kalimat yang sering terdengar oleh para perempuan, terlebih bagi perempuan yang berdarah Jawa.
Perdebatan pun kembali dimulai, apakah harus menjadi perempuan yang di rumah saja atau memilih menjadi perempuan yang berkarir (di luar rumah). Tak hanya sampai disitu, perempuan millenial kekinian pun nyatanya mengalami hangatnya perdebatan, misal saja apakah memilih berpakaian seksi atau berjilbab syar’i, apakah menikah cepat atau lajang lama, apakah begini atau begitu dan banyak lagi perdebatan serta diskursus lainnya. Perempuan sekali lagi menjadi objek sekaligus subjek menarik untuk diperdebatkan, terlebih saat perempuan menjadi satu dari kesekian elemen demografi mayor yang mempengaruhi tingkat elektabilitas dari sebuah kontestasi politik elektoral.